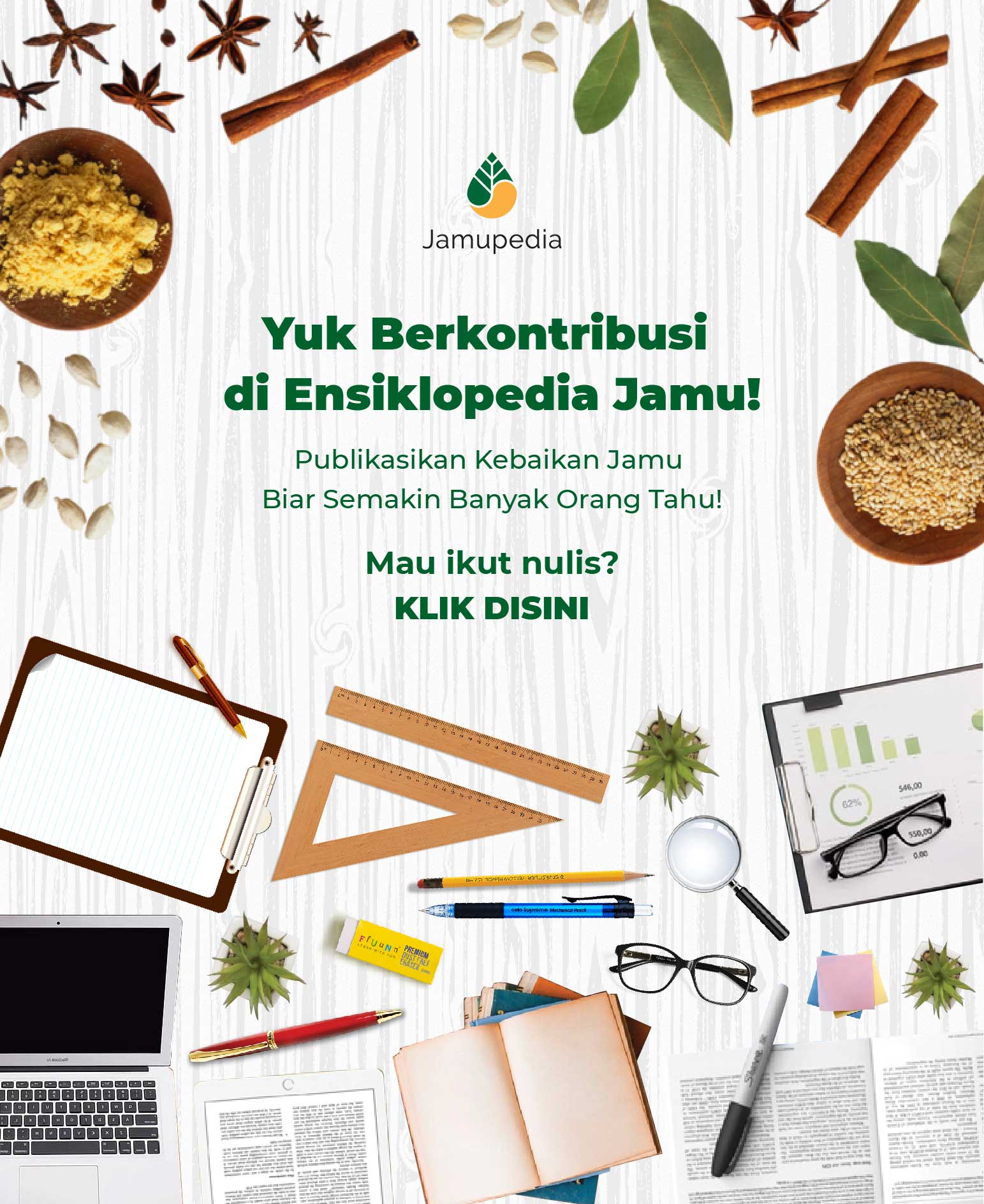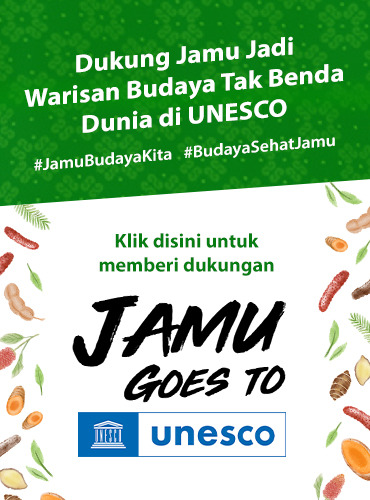Jamu, Warisan Husada Agung Nusantara
"?kalau seorang mengobati tanpa memiliki pengetahuan atau cara mengobati penyakit, namun tetap berusaha menyembuhkan orang sakit hanya demi upah, orang tersebut dapat diperlakukan ibarat pencuri. - Kitab Kutaramanawa Majapahit - "Diterbitkan oleh : Farida - 28/05/2021 18:43 WIB
3 Menit baca.
Tradisi meracik dan mengonsumsi jamu sebagai minuman sehat bagi masyarakat Jawa sudah berkembang sejak masa Hindu-Budha. Data artefaktual pada relief Karmawibhangga di Candi Borobudur abad VIII (pada panel 19), terlihat seorang laki-laki (tampak) sakit memperoleh pijatan di bagian kepala, serta digosok bagian perut sampai dada. Sementara ada yang membawa mangkuk berisi ramuan (racikan jamu) untuk diminum. Selanjutnya ada suasana bersyukur atas kesembuhan seseorang. Selain itu beberapa relief memperlihatkan aneka jenis tanaman seperti nagasari, pinang, jamblang, pandan, kecubung, yang diketahui sebagai tanaman yang sering dipakai untuk meracik jamu. Relief dengan gambaran sejenis juga terdapat di Candi Prambanan, Penataran, Sukuh, dan Tegawangi.

Di masa Kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk telah mengatur secara detail praktek penyembuhan. Pada kitab ‘Kutaramanawa’ disebutkan bahwa praktek penyembuhan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang:
“…kalau seseorang mengobati tanpa memiliki pengetahuan atau cara mengobati penyakit, namun tetap berusaha menyembuhkan orang sakit hanya demi upah, orang tersebut dapat diperlakukan ibarat pencuri.”
Di masa kerajaan Majapahit, Prasasti Balawi (1305 M) juga menyebut profesi tuha nambi (tukang obat), kdi (dukun wanita), serta walyan (tabib). Sementara prasasti Bendosari (1360 M) menyebut ‘janggan’ untuk nama profesi tabib desa. Profesi peracik jamu dan penjual jamu muncul di prasasti ‘Madhawapura’ dengan nama‘acaraki’.
Sebelum kata ‘jamu’ dikenal secara luas, berbagai manuskrip Jawa Kuna menyebut dengan kata oesada (usada) atau ‘jampi’. Kedua kata tersebut sudah disebut pada naskah Gatotkaca Sraya gubahan Mpu Panuluh di era pemerintahan Raja Jayabaya dari kerajaan Kediri. Kata ‘oesada’ lebih mengacu ke arah kesehatan, sementara ‘jampi’ merupakan representasi dari racikan tanaman obat baik dengan cara dikonsumsi atau pengobatan luar disertai (rapalan) doa untuk membantu proses penyembuhan.
Masyarakat Jawa mengenal tiga tingkatan (strata) bahasa, yaitu kromo hinggil (halus), kromo madya, serta ngoko. Perbedaan ini tergantung dengan siapa dan di mana kata tersebut digunakan. Sebagai contoh, ‘Serat Kawruh Bab Jampi – Jampi Jawi’ menjelaskan bahwa penggunaan kata ‘Jampi’ tersebut digunakan oleh lingkaran keraton, dalam hal ini Keraton Surakarta.
Saat diperkenalkan ke luar keraton oleh para wiku dan dukun, maka sesuai strata sosial dan tata bahasa jawa madya dan ngoko kata ‘JAMPI’ berubah menjadi ‘JAMU’. Hal yang sama juga berlaku untuk kata ‘JAWI’ dari tata bahasa kromo hinggil ketika ke luar Keraton kata tersebut berubah menjadi JAWA. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kosa kata JAMU berasal dari Indonesia, khususnya Jawa.
Ulasan mengenai Jamu ada pada Serat Centhini Jilid III kaca 321-330 memuat sekitar 45 jenis tumbuhan tanaman obat untuk meracik 85 macam resep jamu untuk mengobati sekitar 30 jenis penyakit. Sementara itu, pada Serat Kawruh Bab Jampi-Jampi Jawi yang ditulis pada masa Sunan Paku Buwono V tahun 1833, ada sekitar 1.166 resep pengobatan. Jumlah tersebut terdiri dari 922 resep meracik jamu dan 244 resep berupa rajah, jimat, gambar – gambar, doa, rapal, dan mantra sebagai daya penyembuh. Banyaknya jumlah resep pengobatan ini menjelaskan bahwa saat itu masyarakat Jawa sudah memiliki pengetahuan ‘linuwih’ atau unggul dalam seni pengobatan dan penyembuhan penyakit.
Jaya Suprana menempatkan jamu sebagai produk budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu Jamu tidak bisa disejajarkan dengan pengobatan medis lain yang memerlukan prasyarat semacam uji klinis untuk memperoleh legalitas dalam perdagangan. Jamu adalah buah perjalanan sejarah peradaban masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari tali-temali kebudayaan Jawa.
Pemahaman posisi ini penting agar jamu memiliki independensi sebagai kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang telah memberi manfaat kesehatan serta telah dibuktikan melalui perjalanan sejarah peradaban masyarakat Jawa, dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Inilah akar jamu. Inilah kekuatan jamu sebagai produk asli Indonesia.
Jamu Itu Jawa? Bagaimana dengan Wilayah Indonesia Lainnya?
Jamu itu Jawa? Benar jika dikatakan kata jamu berasal dari bahasa Jawa. Namun jamu seperti halnya batik (yang berasal dari bahasa jawa, tetapi penggunaannya juga digunakan untuk komoditas sejenis dari wilayah lain, misalnya Batik Palembang, Batik Cirebon, Batik Papua, dan lain-lain).
Nusantara adalah rumah bagi berbagai jenis tanaman obat dan racikan aneka jamu. Misalnya, pada tahun 1977 sebuah tim peneliti di Kendari, Sulawesi Tenggara menemukan 449 obat herbal yang masih digunakan. Penemuan ini tidak termasuk puluhan campuran herbal yang belum memiliki hak paten dan hanya diketahui penduduk setempat.
Tentu masih banyak lagi jamu-jamu dari berbagai wilayah Indonesia lainnya. Kita bisa lacak kebudayaan jamu-jamu di berbagai wilayah di Indonesia. Pertama Kalimantan, provinsi yang memiliki curah hujan cukup tinggi serta keanekaragaman alam terkaya di dunia. Menurut beberapa literatur, Suku Dayak berhasil mengidentifikasi berbagai tanaman obat yang memiliki sifat untuk penyembuhan. Sedikitnya ada 4.000 spesies tanaman ditemukan di Kalimantan yang memiliki potensi besar untuk obat-obatan baru.
Di Tonsea Minahasa, jamu diracik dengan cara yang sangat sederhana, yaitu berupa ramuan daun segar, tanaman obat yang dikeringkan, ada juga bentuk rebusan, dan ramuan untuk campuran saat mandi seperti preparat asap dan preparat uap. Masyarakat Minahasa terbiasa menggunakan temulawak (tumbulawa), kunyit (kuni), daun tapak kuda (to’dong noat), kumis kucing (makumi nemeong), kencur (sukur), daun sirih (douna), buah pinang (mbua), pare (paria), pala, cengkeh, jahe (sedep), kucai (dansuna kayu), bawang putih (dansuna puti), dan terong (poki-poki) sebagai tanaman obat.
Sejak abad ke-15 Ambon terkenal sebagai pusat perdagangan rempah. Kekayaan alam ini telah menarik perhatian bangsa lain, salah satunya adalah George Everhard Rumphius yang kemudian mengunjungi Ambon dan menulis buku Herbarium Amboinense pada abad ke-17. Buku ini memuat berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Ambon dan Maluku, termasuk tumbuhan rempah, obat, dan sebagainya.
Di Bali kita akan menemukan berbagai lontar-lontar yang berisi berbagai upaya pengobatan tradisional dan ramuan obat. Ramuan tradisional di Bali diracik dengan cara yang sederhana, misalnya tanaman obat diiris-iris tipis kemudian ditempelkan di tempat yang sakit, contohnya bawang putih dan mentimun. Selain itu, ramuan digiling halus kemudian ditempel di tempat yang sakit atau diseduh dengan air mendidih atau direbus atau bisa juga dengan diperas. Bahkan ada beberapa tanaman obat yang dikonsumsi sebagai lalapan. Tanaman-tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Bali tidak banyak berbeda dengan yang digunakan oleh etnis Jawa, seperti jahe, kunyit, sirih, pinang muda, asam kawak, dan masih banyak lagi yang lainnya
Di Madura, kebiasaan minum jamu sudah mendarah daging secara turun temurun. Hingga ada ungkapan di sana: lebih baik tidak makan daripada tidak minum jamu. Jamu tersebut umumnya berupa jamu siap minum yang berupa pil atau seduhan dari bentuk kemasan yang bisa dibisa dibeli di toko-toko jamu. Wanita Madura dan orang Madura pada umumnya lebih menyukai minum jamu berupa seduhan karena lebih kuat dari segi rasa maupun aromanya. Dikatakan pula bahwa khasiatnya lebih nyata daripada minum jamu berupa pil atau serbuk.